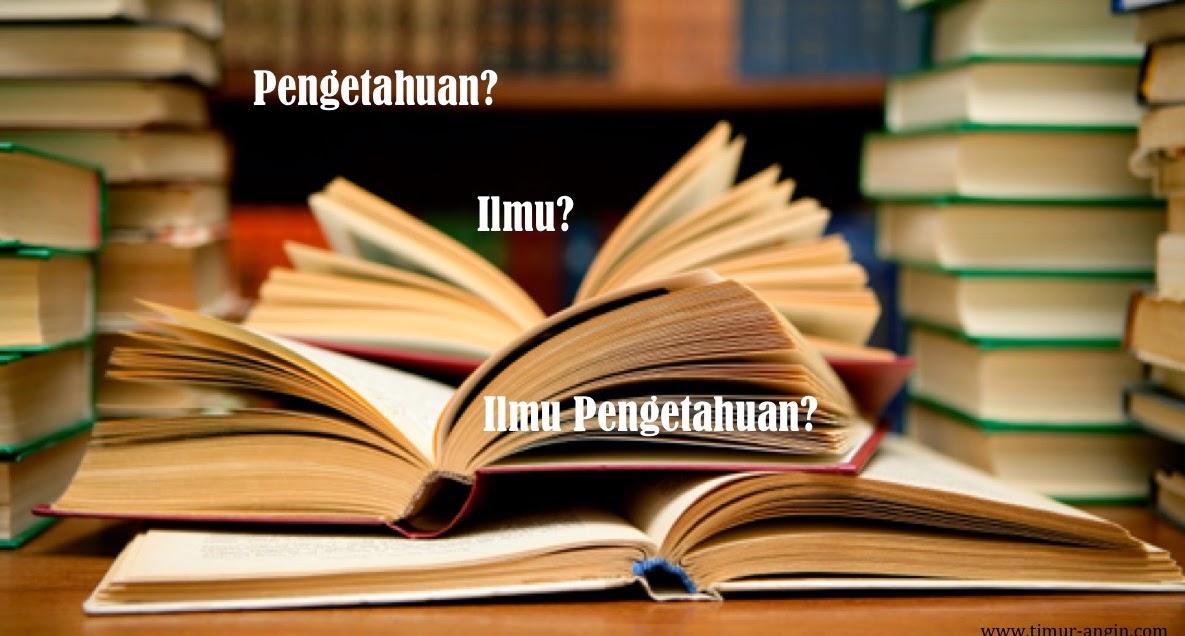oleh: Ahmad Putra Dwitama
Salah satu dari pesan penting di akhir hidup Rasulullah Muhammad Saw.,
kepada semua umat Islam adalah untuk berpegang teguh kepada Alquran dan
Sunnah-sunnah beliau. Barang siapa yang berpegang teguh pada keduanya maka ia
tidak akan tersesat selamanya.
Alquran merupakan suatu kitab yang memancar darinya aneka ragam bentuk
cahaya keilmuan, yang mana dengan pancaran itu fungsinya sebagai petunjuk
kehidupan dapat terwujud. Bagaikan sebuah lilin, tidak akan memancarkan cahaya
sebelum ada usaha untuk menyulut sumbunya. Demikian cahaya Alquran tidak akan
nampak sebelum dibaca, dikaji, serta dipahami.
Dalam upaya memahami Alquran inilah dibutuhkan metode dan ilmu-ilmu yang
mendukung. Para ahli atau yang biasa disebut dengan seorang mufasir pun telah
merumuskan, bahkan dengan panjang lebar, metode dan ilmu yang berkaitan tentang
bagaimana memahami Alquran dengan benar.
Beriringan dengan perjalanan waktu, semakin berkembang ilmu tentang
Alquran. Banyak ahli yang telah menuangkannya dalam bentuk buku secara ringkas
ataupun sampai berjilid-jilid. Intinya, semua mencoba untuk menjelaskan bahwa
dalam memahami Alquran, dibutuhkan alat yang tepat supaya tidak terjadi
penyimpangan penafsiran.
Dewasa ini, didorong dengan motivasi Alquran yang yashluh fi kulli
makan wa zaman (cocok di semua tempat dan waktu), para ahli tafsir dituntut
untuk memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang menimpa umat Islam
khususnya, agar kedudukan Alquran sebagai pemberi cahaya petunjuk tetap pada
fungsinya.
Berangkat dari motivasi tersebut, beberapa ahli mencoba menawarkan
"alat baru" dalam memahami Alquran. Alat yang pada sudut pandang
tertentu mereka sebut sebenarnya, pada dasarnya telah ada pada alat penafsiran
sebelumnya. Juga pada sudut pandang lainnya, dianggap berbahaya jika dipakai
dalam memahami Alquran. Alat tersebut disebut hermeneutika. Hal ini lah yang
dicoba untuk diuraikan oleh penulis dalam makalah singkat ini.
Tafsir
Pengertian Tafsir
Secara etimologi ialah menerangkan dan menyatakan.[1]
Sedangkan Quraish Shihab menerangkan bahwa kata tafsir pada mulanya
berarti penjelasan, atau penampakan makna.[2]
Dalam Alquran disebutkan:
Ÿwur
y7tRqè?ù'tƒ
@@sVyJÎ/ žwÎ) y7»oY÷¥Å_
Èd,ysø9$$Î/
z`|¡ômr&ur #·ŽÅ¡øÿs? ÇÌÌÈ
"Tidaklah orang-orang
kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami
datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya".
Secara terminology, Quraish Shihab mengartikan
tafsir dengan penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan
kemampuan manusia.[3]
Sedangkan menurut al-Kilby dalam al-Tashil
sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy tafsir adalah mensyarahkan
Alquran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nash-nya
atau dengan isyaratnya ataupun dengan najwah-nya.[4]
Dua definisi tersebut sama-sama mendefinisikan
tafsir sebagai kegiatan menjelaskan (mensyarah) Alquran.
Tujuan Tafsir
Mempelajari tafsir memiliki tujuan untuk memahami makna-makna Alquran,
hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, akhlak-akhlaknya dan petunjuk-petunjuk
lainnya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan tafsir seseorang
dapat terhindar dari kesalahan dalam memahami Alquran.[5]
Hukum
Mempelajari Tafsir
Abd. al-Hayy al-Farmawi menyimpulkan, para ulama sepakat bahwa hukum
mempelajari tafsir adalah fardhu kifayah.[6]
Keutamaan
Tafsir
Umat Islam tidak akan bisa bangkit dan meningkatkan martabat hidupnya
melainkan dengan cara mengambil bimbingan serta petunjuk dari ajaran-ajaran
Alquran. Ajaran-ajaran Alquran itu tidak akan dapat dipahami kecuali dengan
mengetahui jalan penafsirannya, mengerti kandungan maknanya, serta cara
memutuskan hukum-hukum dari ayat-ayatnya.[7]
Ditinjau dari aspek tujuannya tafsir memiliki keutamaan untuk selalu
berpegang teguh kepada "tali" agama yang kokoh dan untuk mencapai
kebahagiaan. Dari aspek kebutuhan, kesempurnaan agama dan dunia sangat
memerlukan ilmu agama, sementara ilmu-ilmu agama ini bergantung kepada
pengetahuan tentang Alquran itu sendiri.[8]
Kegunaan
Tafsir
(1)
Mengetahui maksud Allah yang
terdapat dalam syariat-Nya.
(2)
Mengetahui petunjuk Allah mengenai
akidah, ibadah, akhlak dsb.
(3)
Mengetahui kemukjizatan Alquran.
(4)
Menyampaikan seseorang ke derajat
ibadah yang paling baik.[9]
Syarat-syarat
Penafsir
(1)
Memiliki i'tikad yang benar dan
mematuhi segala ajaran agama
(2)
Mempunyai tujuan yang benar
(3)
Seorang penafsir seyogyanya hanya
berpegang kepada dalil naqli dari nabi, sahabat, dan orang-orang yang hidup
sezaman dengan mereka, serta harus menghindari segala sesuatu yang tergolong
bid'ah[10]
(4)
Menguasai ilmu-ilmu yang
diperlukan:
a.
Ilmu Bahasa Arab
b.
Ilmu Nahwu
c.
Ilmu Sharaf
d.
Pengetahuan tentang isytiqaq (akar
kata)
e.
Ilmu al-Ma'any
f.
Ilmu al-Bayan
g.
Ilmu al-Badi'
h.
Ilmu al-Qira'at
i.
Ilmu Ushul al-Din
j.
Ilmu Ushul al-Fiqh
k.
Asbab al-Nuzul
l.
Nasekh dan Mansukh
m.
Fiqih/Hukum Islam
n.
Hadis-hadis nabi yang berkaitan
dengan penafsiran ayat
o.
Ilmu al-Mauhibah.[11]
Metode Tafsir
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwa tafsir ialah penjelasan
tentang maksud-maksud Allah dalam firman-Nya sesuai dengan kemampuan manusia.
Dari kata penjelasan, lahir pemahaman bahwa ada sesuatu yang dihidangkan
sebagai penjelasan serta cara menghidangkan penjelasan itu. Dari kalimat sesuai
kemampuan manusia tersirat keanekaragaman penjelasan dan caranya.[12]
Terdapat beberapa metode tafsir yang dikenal dengan beragam macam cara
penyajiannya:
(1)
Tahlily/Analisis
(2)
Ijmaly/Global
(3)
Muqarin/Perbandingan
(4)
Maudhu'i/Tematik.[13]
Hermeneutika
Ringkas
Tentang Hermeneutika dan Pokok Bahasannya
Sebagian perbincangan tentang problem hermeneutika modern terletak pada
kesulitan menempatkan suatu definisi hermeneutika yang dapat disepakati
bersama. Banyak usaha telah dilakukan untuk menganalisis makna verbal hermeneutika
yang cocok dengan istlah Inggris hermeneutics dan dengan verba Latin interpretari
dalam rangka memperoleh definisi yang diinginkan. Sebagian upaya juga
didedikasikan untuk menemukan perbedaan-perbedaan etimologis antara hermeneuein
dan exegeisthai yang dapat menyajikan titik terang perbedaan antara
hermeneutika dan eksegesis (penafsiran).[14]
Secara ringkas hermeneutika mempunyai tiga makna: pertama adalah
mengungkapkan, menafsirkan atau menjelaskan; yang kedua adalah
menerjemahkan, dan makna hermeneutika yang ketiga dapat digambarkan
sebagai "mentransmisikan pemahaman" dan "membuat paham",
baik melalui tuturan bebas, menafsirkan sesuatu yang telah dibicarakan, atau
menafsirkan melalui terjemahan.[15]
Menurut Quraish Shihab, hermeneutika adalah alat-alat yang digunakan
terhadap teks dalam menganalisis dan memahami maksudnya serta menampakkan nilai
yang dikandungnya. Jelas bahwa yang menjadi pokok bahasan hermeneutika adalah
teks, terutama teks-teks lama yang menyangkut masalah sejarah atau agama.[16]
Masih menurut pemaparan Quraish Shihab, bahwa hermeneutika berasal dari kata hermenium
(Bahasa Yunani) yang berarti penjelasan, penafsiran, penerjemahan. Ada
juga pendapat bahwa hermeneutika ada kaitannya dengan Hermes yang
diyakini sebagai sosok pembawa berita dari para dewa untuk selanjutnya
dijelaskan pada manusia. Bahkan ada yang menyatakannya sebagai Nabi Idris as.[17]
Objek Kajian
Pada awalnya, hermeneutika diadopsi oleh sebagian kalangan cendikiawan
Kristen Protestan sekitar tahun 1654 M. Hermeneutika dijadikan alat atau seni
interpretasi Perjanjian Lama dan Baru. Dewasa ini, objek kajiannya pun
berkembang, dari kitab suci umat Kristiani, kemudian mencakup bidang-bidang
humaniora, seperti sejarah, sosiologi, antropologi, filsafat, estetika, dan
folklor.[18]
Fungsi
Mempelajari Hermeneutika
Drs. M. Munir menjelaskan, fungsi dari memperlajari hermeneutika antara
lain:
(1)
Menjelaskan ide dalam pikiran
melalui kata-kata
(2)
Menjelaskan makna yang masih samar
menjadi lebih jelas
(3)
Menerjemahkan suatu bahasa ke
dalam bahasa lain yang lebih dikuasai
(4)
Mencari makna yang relevan dan
kontekstual di era sekarang
Hermeneutika akan membawa pemakainya kepada sifat skeptis. Berbagai
pertanyaan akan muncul seperti apakah hakikat teks? Apa makna pemahaman dan
penafsiran? Apa hubungan teks dengan budaya, sejarah, dan peninggalan lama? Apa
hubungan teks dengan pemilik (pengucap/penulis teks)? Pertanyaan serupa, jika
dibawa kepada Alquran; apa hakikat ayat Alquran ini? Siapa pengarangnya?
Bagaimana kondisi si pengarang? Apa tujuan si pengarang?
Dari sikap tersebut juga dapat memberi sisi positif antara lain:
(1)
Dapat melahirkan makna actual
sebuah teks
(2)
Mendekatkan teks dengan para
pembaca
(3)
Mengeliminir mistikasi penafsiran
kitab suci
(4)
Lebih terukur
(5)
Lebih lentur/ fleksibel
Beliau juga mengingatkan, mengutip pemaparan Abdul Mustaqim, dalam
mempelajari dan menerapkan hermeneutika terhadap Alquran perlu memperhatikan
hal-hal berikut:
(1)
Jangan menggugat otoritas Alquran
(2)
Tetap menjaga dan menghargai
pemikiran ulama masa lampau
(3)
Menjaga hal-hal yang sudah tsawabit
(tetap).[19]
Pro dan
Kontra Hermeneutika Pada Alquran
Alasan kelompok yang menerima hermeneutika dalam pemikiran Islam adalah
sebagai berikut:
(1)
Alquran adalah teks-teks manusia
biasa (hasil dari kebudayaan) dank arena itu perlu adanya interpretasi agar
dapat dipahami
(2)
Alquran kini sudah saatnya
ditafsirkan ulang, karena tafsir Alquran yang ada sekarang hanya ditafsirkan
secara tekstual, maka perlu adanya penyesuaian dengan kondisi (konteks) masa
sekarang
(3)
Penafsiran Alquran yang ada ini
masih relative kebenarannya. Sehingga masih memungkinkan penafsiran-penafsiran
yang lebih bebas dari itu
(4)
Unsur pokok yang menjadi pilar
utama hermeneutika: tekt, author, dan audience, tidak berbeda
dengan konsep tafsir Alquran yaitu: 1) siapa yang mengatakan, 2) kepada siapa
diturunkan, dan 3) ditujukan kepada siapa.
(5)
Praktek hermeneutika telah
dilakukan dalam dunia penafsiran Islam sejak lama, bahkan sejak awal kajian
tafsir, khururnya ketika menghadapi Alquran. Bukti hal itu adalah: 1)
kajian-kajian mengenai asbab nuzul dan nasikh-mansukh, 2)
penggunaan berbagai teori dan metode dalam proses penafsiran, dan 3) adanya
kategorisasi tafsir tradisional seperti; tafsir syi'ah, tafsir mu'tazilah,
tafsir hukum, tafsir filsafat, dan lain-lalin. Ini menunjukkan kesadaran
tentang kelompok, ideology, periode, maupun horizon sosial tertentu.
(6)
Istilah hermeneutika dalam
pengertiannya hampir sama dengan istilah tafsir atau takwil yang berarti
menerangkan atau mengungkap, sedang hermeneutika memiliki pengertian
interpretasi.
(7)
Ada kesejajaran antara semangat
Reformasi Protestan dan Gerakan Salafiyah dalam Islam. Dalam gerakan salafiyah,
dikembangkan suatu tradisi penafsiran Alquran yang kurang labih independen dari
tradisi mazhab. Inilah yang menjelaskan kenapa dalam keputusan-keputusan majlis
tarjih Muhammadiyah misalnya, rujukan kepada Kitab Kuning yang memuat khazanah
tradisi bermazhab sama sekali kurang, atau malah tak ada sama sekali.
Sedangkan kelompok yang menolak hermeneutika dalam kajian Islam, memiliki
alasan sebagai berikut:
(1)
Hermeneutika berlandaskan pada
pedoman bahwa segala penafsiran Alquran itu relatif. Padahal, fakta menunjukkan
bahwa para mufasir sepanjang masa tetap memiliki pedoman-pedoman pokok dalam
menafsirkan Alquran
(2)
Pemegang hermeneutika berpendapat
bahwa penafsir bisa lebih mengerti lebih baik daripada pengarang, mustahil
dapat terjadi dalam Alquran. Tidak pernah ada seorang mufasir Alquran yang
mengklain bahwa dia lebih mengerti dari pencipta atau pengarang Alquran.
(3)
Konsep hermeneutika yang
berpedoman bahwa interpretasi teks yang berdasarkan doktri dan bacaan yang
dogmatis harus ditinggalkan dan dihilangkan (deabsolutisasi) juga tidak sesuai
dengan ajaran Islam. Umat Islam diajarkan untuk meyakini bahwa Alquran adalah
sebuah mukjizat dan berbeda dengan teks-teks biasa. Doktrin kebenaran Alquran
semuanya bersumber kepada Allah dan menjadi syarat keimanan umat Islam.
(4)
Pemegang hermeneutika mengatakan
bahwa pengarang tidak mempunyai otoritas atas makna teks, tapi sejarah yang
menentukan maknanya juga tidak mungkin diaplikasikan pada Alquran. Seluruh umat
Islam sepakat bahwa otoritas kebenaran Alquran tetap dipegang oleh Allah
sebagai penciptanya. Realita juga menunjukkan bahwa Allah melalui Alquran
justru mengubah sejarah, bukan dipengaruhi atau ditentukan oleh sejarah. Di
antara pengaruh Alquran adalah fakta bahwa Alquran telah melahirkan sebuah
peradaban baru yang disebut sebagai "peradaban teks".
(5)
Tradisi hermeneutika dalam bible
memang memungkinkan. Terdapat berbagai macam Bible dan tiap-tiap Bible ada
pengarangnya. Tapi teks Alquran pengarang hanyalah Allah. Karena itu
hermeneutika yang diaplikasikan pada Bible tidak mungkin digunakan dalam
Alquran.
(6)
Bible diliputi serangkaian mitos
dan dogma yang menyesatkan. Hal tersebut memicu digunakannya hermeneutika
terhadap Bible. Sedangkan Alquran itu pasti dan terjaga status keasliannya.
Begitu pula sejarah dan tradisi tafsir Alquran. Karena Alquran diciptakan oleh
zat yang Maha Sempurna dan ditafsirkan oleh makhluk yang penuh keterbatasan,
maka tidak akan pernah ada kata sempurna tentang penafsirannya.
(7)
Orang yang ingin menafsirkan
Alquran harus memenuhi beberapa syarat ketentuan seperti yang telah diungkapkan
sebelumnya. Hal ini tidak berlaku untuk hermeneutika.[20]
Perbedaan Tafsir dan Hermeneutika
Alquran sebagai sebuah kitab suci dan pedoman hidup kaum Muslimin, telah,
sedang, dan akan selalu ditafsirkan. Karena itu dalam pandangan kaum Muslim
tafsir Alquran adalah istilah yang sangat mapan. Bagaimanapun, akhir-akhir ini
istilah hermeneutika Alquran (Quranic hermeneutic) sering digemakan oleh para
orientalis dan para pemikir Muslim modernis seperti Hassan Hanafi, Fazlur
Rahman, Mohamed Arkoun, Nars Hamid Abu Zayd, Amina Wadud Muhsin, Ashgar Ali
Engineer, Farid Esack, dan lain-lain. Padahal istilah hermeneutika adalah kosa
kata filsafat Barat, yang juga sangat terkait dengan interpretasi Bible.
Dari pemaparan sebelumnya, dapat ditulis beberapa perbedaan antara tafsir
dan hermeneutika sebagai berikut:
No.
|
Tafsir
|
Hermeneutika
|
1
|
Memiliki konsep yang jelas, berurat serta berakar dalam
Islam
|
Dibangun atas faham relatifisme dan skeptisisme
|
2
|
Para mufasir yang terkemuka sepanjang masa tetap memiliki
kesepakatan-kesepakatan
|
Menggiring kepada gagasan bahwa segala penafsiran Alquran
itu relative
|
3
|
Merujuk kepada ilmu yang dengannya dilakukan pemahaman
terhadap Kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, penjelasan mengenai
makna-makna dan penarikan hukum berserta hikmahnya diketahui
|
Diasosiasikan kepada Hermes, seorang utusan dewa dalam
mitologi Yunani Kuno yang bertugas menyampaikan dan menerjemahkan pesan
Dewata yang masih samar ke dalam bahasa yang dipahami manusia
|
4
|
Sumber epistemology adalah wahyu Alquran
|
Sumber epistemology dari akal yang membawa pada dugaan,
keraguan, dan asumsi
|
5
|
Sejarah tafsir yang sudah begitu mapan dalam Islam
|
Muncul di dalam konteks peradaban Barat, yang didominasi
oleh konsep ilmu yang skeptic atau spekulasi akal
|
6
|
Ilmu pendukung dalam menafsirkan Alquran sudah ada dan
mapan
|
Tidak ada ilmu pendukung hermeneutika.[21]
|